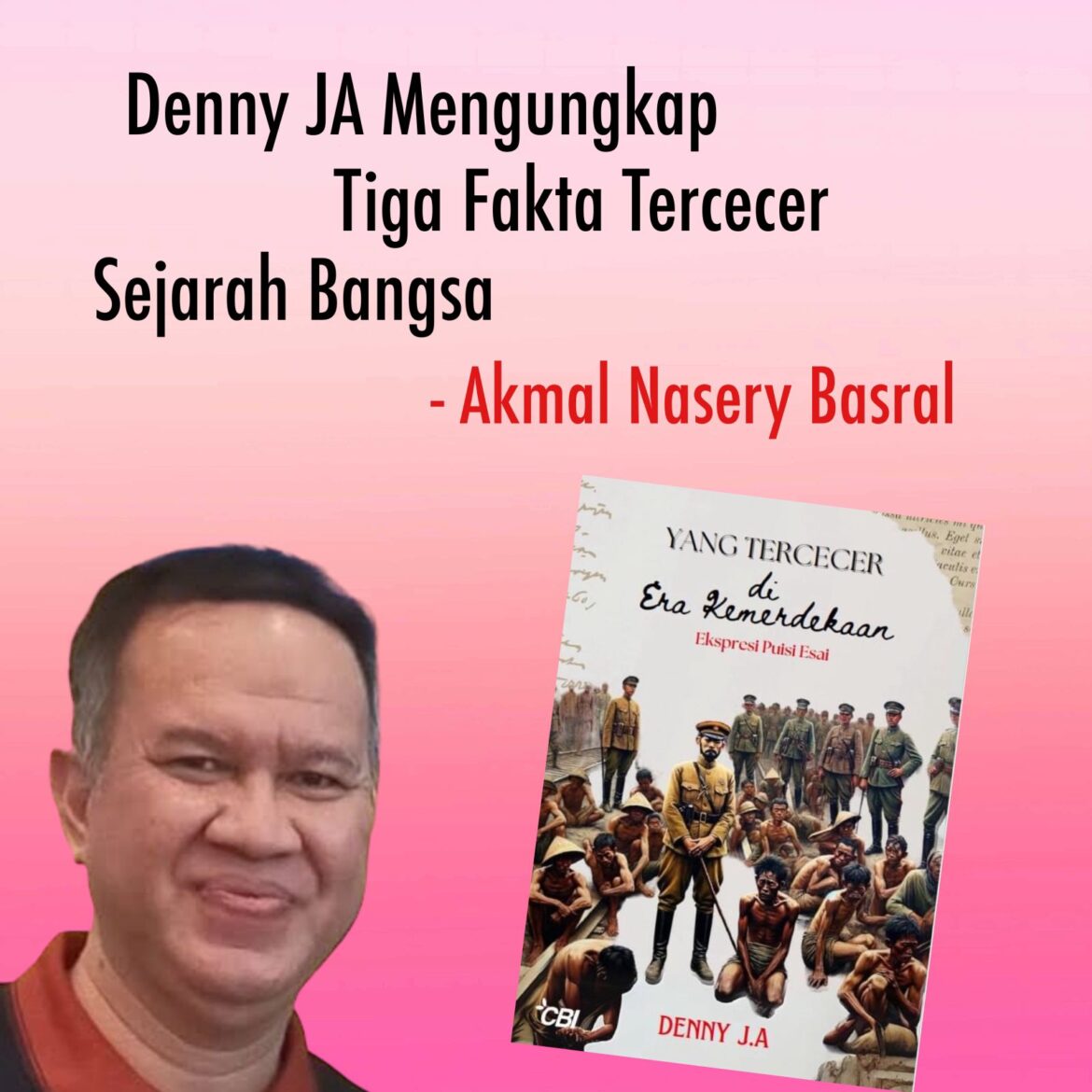DENNY JA MENGUNGKAP TIGA FAKTA TERCECER SEJARAH BANGSA
Oleh Akmal Nasery Basral
1/
JIKA sejarah adalah peti besar misterius penuh debu dengan kunci berkarat yang teronggok di sudut gudang, maka penulis adalah sosok yang tak pernah meletih berikhtiar agar peti dibuka supaya isinya diketahui khalayak. Betapapun pahit rahasia yang tersembunyi di dalamnya membuat jiwa cabik bahkan terkoyak.
Itu _aftertaste_ literer yang saya rasakan usai membaca _Yang Tercecer di Era Kemerdekaan: Ekspresi Puisi Esai_ (Cerah Budaya Indonesia, Juni 2024), karya terbaru Denny J.A sang pengibar bendera puisi esai dalam lanskap sastra.
Dikemas dalam format buku elektronik ( _e-book_) setebal 92 halaman dan didistribusikan cuma-cuma melalui platform media sosial Facebook dan WhatsApp, _Yang Tercecer_ sangat relevan difungsikan sebagai cermin bangsa yang sedang gegap gempita merayakan hari kemerdekaan ke-79 kemarin hingga akhir bulan.
Melalui kumpulan puisi esai keenam ini, Denny sang doktor ilmu politik alumnus Universitas Ohio State, seakan membangun portal perjalanan ke masa silam menuju jantung lubang hitam ( _black hole_) semesta derita bangsa.
Sebuah perjelajahan internal dan historikal yang–mau tak mau, suka tak suka–harus diambil hikmahnya agar tak terulang menjadi kutuk masa depan seperti diingatkan Milan Kundera tentang bangsa yang abai dengan sejarahnya akan mengalami lagi derita serupa.
_Yang Tercecer_ terdiri dari tiga tema yang membuat bulu kuduk pembaca meremang akibat bergidik ngeri, yakni (1) “Kisah Gadis Pribumi yang Dipaksa Menjadi Penghibur Tentara Jepang”, (2) “Kisah Derita Rakyat yang Kerja Paksa”, dan (3) “Kisah Para Nyai dan Gundik Tuan Belanda”.
Setiap tema dibangun melalui lima karya yang saling jalin berkelindan. Ada dramatisasi pada setiap karya, namun bahan utamanya tetap peristiwa dan fakta yang terjadi pada era kolonialisme Belanda dan Jepang di tanah air tercinta.
Pada bagian pertama tentang nestapa para perempuan yang dipaksa menjadi budak seks pemuas nafsu (Jepang: _jugun ianfu_) prajurit Negeri Matahari Terbit.
Pembaca bertemu dengan Rahma (“Jangan Panggil Aku Gadis Penghibur”), Rara (“Rara Masih Mencari Sari”), Nenek Bambang (“Mencari Makam Nenek”), Sonya (“Lima Puluh Tahun Kututup Rahasia Itu Rapat-Rapat”), dan Sakinah (“Luka Itu Dibawanya Hingga Mati”).
Lima perempuan yang terjerumus dalam jebakan propaganda iming-iming kesempatan kerja di Kalimantan untuk kehidupan yang lebih baik, namun berakhir menjadi sasaran pelampiasan syahwat kebinatangan.
Dalam sehari, seorang _jugun ianfu_ seperti Rahma dan Sonya bisa didatangi 10 – 15 prajurit Kaisar Dewa Matahari yang melakukan rudapaksa kapan saja.
Bukan hanya para perempuan Indonesia yang menjadi korban mereka, juga para dara tak berdaya dari Filipina, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan. Sedikitnya 200.000 perempuan menjadi vandalisme kejantanan selama penjajahan Bala Tentara Jepang di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara di era Perang Dunia II.
Pada 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama menyampaikan permintaan maaf atas perilaku tentara mereka itu. Namun sampai dunia memasuki milenium ketiga, politisi seperti Walikota Osaka, Toru Hashimoto, masih membela laku bejat itu dengan alasan “daripada Tentara Jepang memperkosa penduduk, lebih baik disediakan rumah bordil. Itu bagian disiplin Tentara Jepang.” (hal. 22). Maka dibuat rasio 70: 1 atau untuk setiap 70 orang prajurit disiapkan seorang _jugun ianfu_ pelepas syahwat.
Sebagai penyair puisi esai, Denny J.A. menggambarkan fragmen kedukaan personal para _jugun ianfu_ dengan pilihan frasa yang membuat sesak napas pembaca. Misalnya pada kalimat berikut ini:
_sebelum Rahma mati di tahun 2007/Rahma sudah menguburkan dirinya sendiri_ (“Jangan Panggil Aku Gadis Penghibur’, hal. 4).
Atau kalimat ini: _Luka batin Sakinah karena dipaksa menjadi gadis penghibur tetap menganga/Namun ternyata ada luka yang lebih perih/Hingga suaminya wafat Sakinah tak berani memberi tahu/bahwa dirinya dulu pernah dipaksa menjadi gadis penghibur tentara Jepang_. (“Luka Itu Dibawanya Hingga Mati”, hal. 20).
Denny tak menggunakan diksi atau ungkapan metaforis demi mengejar puncak-puncak estetika bahasa, melainkan memilih stilisasi ekspresi yang tak akan menimbulkan perbedaan pemahaman di benak pembaca.
2/
BAGIAN kedua bertema “Kisah Derita Rakyat yang Kerja Paksa” adalah cuplikan cerita para romusha, lelaki pekerja proyek infrastruktur yang membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan aneka proyek konstruksi lainnya.
Lima puisi esai dalam topik ini membuat pembaca bertemu dengan Samin (“Samin Terkapar di Anyer – Panarukan”), Joko (“Wahidin dan Rel Kematian”), Bayu (“Mencari Kakek di Hutan Kalimantan”), Ampong (“Atas Nama Dewi Keadilan”), dan Bambang (“Pulang Kampung Mencari Kenangan”).
Jika bagian pertama membuat air mata pembaca berderai-derai—paling tidak membuat mata basah berkabut—maka bagian kedua membuat ulu hati mual bercampur rasa geram atas kebiadaban yang dibenarkan atas nama penjajahan. Atas nama pembangunan.
Pada kisah Samin yang menjadi seorang romusha pembangunan Jalan Raya Pos Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km dan menelan nyawa ribuan pekerja, Denny menulis: _Tapi 12 ribu orang mati karena membuat jalan ini. Ini sejenis genosida atas nama pembangunan_. (hal. 27).
Kalimat Denny ini mengingatkan saya pada sebaris larik puisi dramawan masyhur Jerman, Bertolt Brecht (1898 – 1956) yang berbunyi: _pada malam Tembok Tiongkok berdiri, ke manakah para tukang batu pergi?
Ada kegetiran eksistensial yang serupa pada kalimat Denny dan Brecht. Bahwa untuk setiap keberhasilan proyek mercu suar yang berkibar, fondasinya adalah tumpasnya ribuan nyawa manusia dalam keadaan teraniaya secara barbar.
Bagian ketiga antologi puisi esai ini mengusung tema “Kisah Para Nyai dan Gundik Tuan Belanda”, kembali akan membuat mata pembaca menjadi telaga air mata setelah mengetahui bagaimana nasib para perempuan Indonesia hanya menjadi properti di dalam dunia patriarki yang didominasi hegemoni para lelaki bertubuh tonjang, berambut pirang, yang datang dari berbilang samudera seberang. Mereka menjadi tuan dan penguasa atas tubuh molek gadis-gadis khatulistiwa.
Denny menggambarkan tanpa tedeng aling-aling: _Kerja Nyai, melayani Tuan Belanda/Melahirkan anak/Tapi Nyai tak punya hak atas anak yang dilahirkannya/Tuan Belanda bisa membawa anak itu kapan saja/Hukum Belanda tak melindungi Nyai/Masyarakat Belanda melihat Nyai bukan warga setara/Beda agama/Beda pendidikan/Beda status pendidikan/Beda kelas._ (“Gadis Belanda Mencari Neneknya di Cimahi”, hal. 52 – 53).
Namun, Denny tak selalu menggunakan bahasa lugas gamblang. Terkadang digunakannya juga pola repetisi yang—untungnya—berhasil memperkuat kekuatan makna seperti pada bagian ini:
_Arthur memang menyayanginya_
_Terasa_
_Tapi Asih merasa sepi_
_Terasa_
_Istri dan anak Arthur memusuhi_
_Terasa._
(“Nyai Asih Ikut ke Belanda”, hal. 63-64).
3/
Sejak Denny J.A. mengibarkan ‘bendera’ puisi esai dalam ranah sastra nasional melalui antologi perdana _Atas Nama Cinta_ (2012), butuh waktu satu windu bagi puisi esai sebelum menjadi lema resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang mendefinisikan sebagai ‘jenis puisi yang mengandung pesan sosial dan moral melalui kata-kata sederhana dengan pola berbait-bait berupa fakta, fiksi dan catatan kaki’.
Puisi esai menjalani metamorfosisnya dalam 12 tahun perjalanannya hingga tahun ini. Ada setidaknya dua perbedaan format puisi esai periode awal dan periode sekarang, sependek pengamatan saya.
Pertama pada panjang puisi atau durasi pembacaan jika dibawakan di atas panggung. Jika puisi esai periode awal seperti _Atas Nama Cinta_ dibawakan para dramawan dan sastrawan Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri atau Sujiwo Tejo, maka satu karya membutuhkan waktu 30 – 40 menit pembacaan.
Sementara, karya-karya pada _Yang Tercecer_ ini jauh lebih singkat karena hanya membutuhkan waktu 5-10 menit pembacaan.
“Memang niat saya untuk semakin melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat agar lebih mengakrabi puisi esai. Salah satunya melalui durasi yang diperpendek tanpa mengurangi relevansi pesan yang disampaikan,” ungkap Denny J.A. kepada saya dalam sebuah pembicaraan.
Perbedaan kedua antara puisi esai format terdahulu dan format terkini terletak pada cara penulisan catatan kaki.
Jika sebelumnya catatan kaki ditulis secara konvensional layaknya dalam konvensi penulisan artikel ilmiah, maka sekarang digantikan dengan gambar QR ( _Quick Response_) Code yang canggih.
Ini sangat memudahkan bagi pembaca yang tertarik ingin menelusuri lebih jauh referensi faktual atas puisi esai yang tersaji. Misalkan pada puisi esai “Lima Puluh Tahun Kututup Rahasia Itu Rapat-Rapat” yang menggambarkan penderitaan Sonya sebagai _jugun ianfu_, sebelum dinikahi seorang tentara Inggris usai Perang Dunia II.
Jika QR Code yang disertakan pada akhir puisi esai ini digunakan pembaca, maka akan muncul tautan sumber berita obituari pada harian _The Washington Post_ berjudul “ _Jan Ruff O-Herne, Seeker Dignity for Fellow ‘Comfort Women’ of World War II, Dies at 96”_ (27 Agustus 2019).
‘ _Comfort women_’ (wanita penghibur) adalah padanan dalam Bahasa Inggris untuk Bahasa Jepang _jugun ianfu_.
Jan Ruff (terlahir dengan nama Jeanne Alida O’Herne), lahir 18 Januari 1923, dari sebuah keluarga Belanda penganut Katolik yang taat di Bandung. Hidupnya bahagia dan bercita-cita menjadi biarawati, sampai masuknya Jepang ke Indonesia dan para gadis dibariskan para serdadu.
Jan termasuk 1 dari 10 orang dara cantik yang diambil paksa dan dipisahkan dari keluarganya, untuk menjalani kehidupan sebagai _jugun ianfu_. Sejak itulah garis hidupnya berubah total.
Dari kisah obituari mengiris hati yang diwartakan _The Washington Post_ itulah Denny J.A. mengolahnya menjadi sebuah karya puisi esai yang bertenaga. Sekaligus membuat galau pembaca.
Bagi Anda peminat sejarah Indonesia, khususnya tema-tema _jugun ianfu_, romusha, dan kehidupan para nyai yang dijadikan gundik para Tuan Belanda, antologi _Yang Tercecer di Era Kemerdekaan: Ekspresi Puisi Esai_ adalah karya yang harus dibaca.
Setidaknya puisi esai ini sebagai penyadaran bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak hanya berkat perjuangan mereka yang mendapat gelar pahlawan nasional, melainkan juga akumulasi pengorbanan dan nestapa tiada tara dari entah berapa banyak rakyat jelata. ***)
Posted: sarinahnews.com
Cibubur, August 18, 2024
Kritik Sastra: Puisi Esai ditulis oleh Akmal Nasery Basral, (Sosiolog, Penerima Anugerah Sastra Andalas 2022 kategori Sastrawan/Budayawan Nasional)
Catatan:
Kumpulan puisi esai terbaru Denny J.A. yang menyajikan pengalaman hitam bangsa, yang nyaris terlupakan dalam eforia perayaan kemerdekaan ke-79
Buku puisi esai Denny JA “Yang Tercecer di Era Kemerdekaan” bisa dibaca melalui link:
https://www.facebook.com/share/p/Bh4JmuhmtrvHLVt6/?mibextid=K35XfP